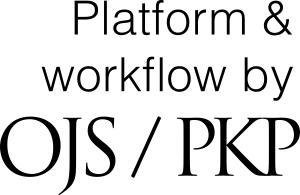| MENU UTAMA |
| Tentang Jurnal |
| Tim Editorial/Penyunting |
| Etika Publikasi |
| Informasi Kontak |
| Edisi Ini |
| Arsip Terbitan |
| Flowchart Pengiriman & Proses Artikel |
| Unduh Template Artikel |
| Daftar/Submisi |
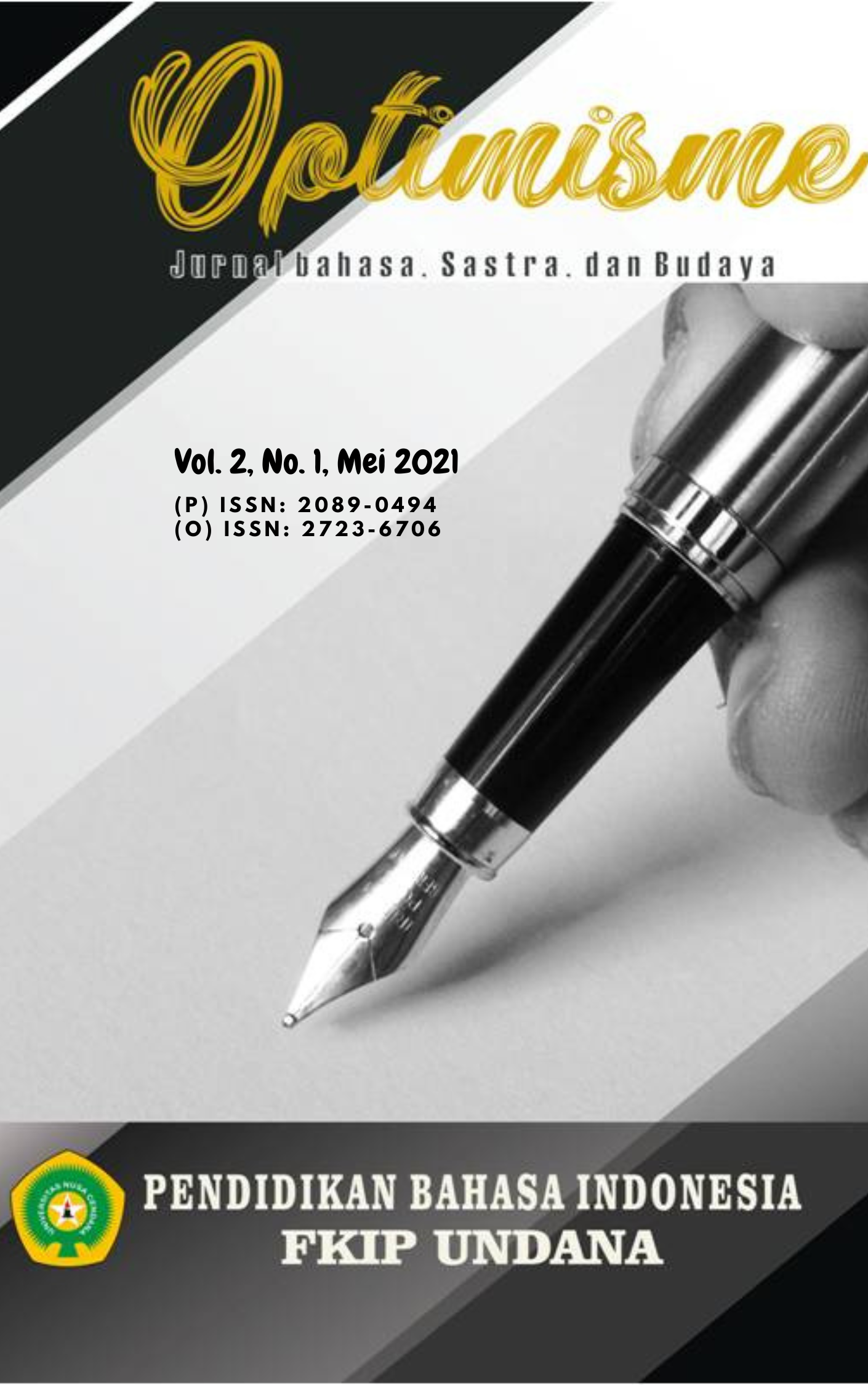
DARI REDAKSI
EDISI MEI 2021
Bahasa dan Ideologi
Edisi Optimisme kali ini lahir, ketika konflik antara Israel dan Hamas (Pelestina) lagi akut.
Telah banyak nyawa yang direngguk akibat konflik tersebut. Upaya gencatan sejanta telah
dilakukan. Namun, gencatan kata, kalimat, dan wacana tidak dilakukan. Malahan, wacana (baca
media) terus menggemburkan dan menghamburkan suasana horor. Akibatnya, sebagian kecil
masyarakat kesurupan dan memaki-maki kelompok tertentu. Kita begitu gampang terperosok
dalam dua kubu itu. Padahal, kita bukan siapa-siapa. Bukan intelejen, bukan pula kedubes
Indonesia untuk Israel dan Palestina. Namun, kita terkesan tahu tentang kasus kedua negara itu.
Israel dan Palestina datang kepada kita melalui pihak ketiga, yakni media massa. Artinya, pose
Israel dan Palestina di hadapan kita melalui kata, frasa, kalimat, dan wacana yang telah
dikontruksi secara sistematis oleh jurnalis. Para jurnalis mengontruksi realitas menjadi realitas
verbal, atau sering disebut dengan realitas kedua (second reality). Unsur elementer untuk
mengubah realitas pertama (realitas sebenarnya) menjadi realitas kedua (realitas verbal) adalah
bahasa.
Bagaimana jurnalis menggunakan bahasa untuk mengubah realitas ini? Pertanyaan ini
hanya mendapat jawaban bila kita melakukan konfirmasi dengan teori Analisis Wacana Kritis.
Norman Fairclough atau Teun van Dijksecara tegas mengatakan, wacana tidak cukup paham
sebagai satuan lingual yang mengandung arti, tetapi merupakan alat ungkap ideologi dan
kekuasaan. Bahasa tidak pernah netral. Ia telah disusupi oleh ideologi. Seorang jurnalis dengan
haluan politik tertentu, dapat menulis kalimat, “Tariq Ismail meninggal diterjang peluruh tentara
Israel.”Jurnalis lain menulis, “Anak-anak Palestina meninggal diterjang peluruh tentara Israel.”
Secara tekstual, arti kedua kalimat itu, kurang lebih sama. Namun, secara wacana sangat berbeda.
Kalimat pertama, menunjukkan oknum (hanya seorang). Sedangkan kalimat kedua menunjukkan
kelompok atau jumlah yang besar, “anak-anak palestina.” Kalimat kedua mengandung bias
nominal (nominalisasi). Tentu, masih banyak lagi peranti kebahasaan yang menjadi instrumen ideologis. Ini yang sering saya sebut sebagai manuver tekstual atau yang disebut pula dengan
sistem pembingkaian (framing). Pembaca sengaja dikerangkeng dalam pembingkaian bahasa
jurnalis. Problem itulah yang sedang melanda masyarakat kita. Betapa jarang kita mencoba
melakukan pembandingan (literasi) bagai pemberitaan media di Indonesia dengan media di
Australia, Amerika, atau Arab seklipun.
Kita mengetahui konflik Israel dan Hamas (Palestina) melalui pihak ketiga tadi (media massa).
Kita tentu diminta cerdasa membaca media tidak hanya satuan lingual (informasi), melainkan
ideologi di baliknya. Karena itu, gencatan senjata, hanya menjadi ironi bila tidak diikuti dengan
gencatan kata. Apakah dalam perang apapun sangat sulit melakukan gencatan kata? Padahal, kata
jauh lebih tajam dari pedang atau senjata. Napoleon Bonaparte (1769-1821, Kaisar Perancis) dan
panglima perang sejagat itu pernah berkata, “Saya lebih takut seorang wartawan daripada seribu
serdadu.”
Redaksi
Marselus Robot